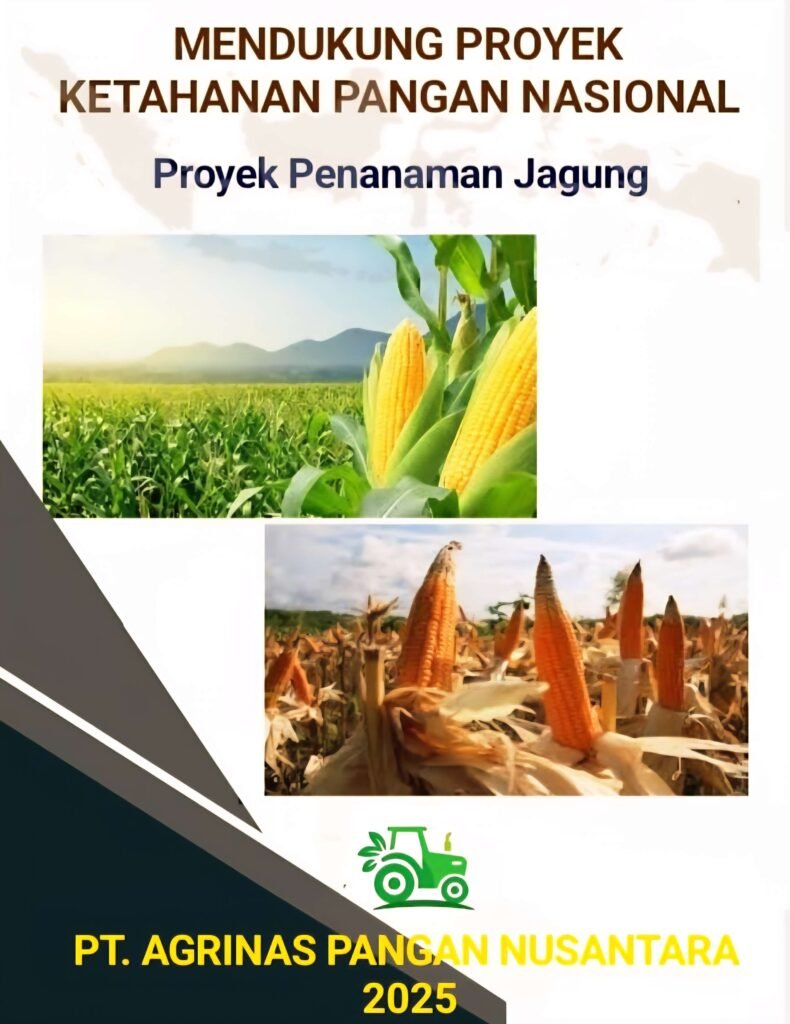NusantaraBaru | Hujan deras yang turun dari langit seharusnya menjadi berkah bagi bumi, menyirami tanah dan menghidupkan kehidupan.
Namun, di Sumatera Utara, hujan justru menjadi malapetaka.
Banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah ini baru-baru ini, pada 25-26 November 2025, telah menewaskan setidaknya 24 orang, melukai puluhan lainnya, dan memengaruhi 11 kabupaten/kota dengan total 86 kejadian bencana, termasuk 59 longsor, 21 banjir, dan 4 pohon tumbang.
BNPB mencatat bahwa sepanjang 2025, banjir di Sumatera Utara telah terjadi sebanyak 75 kali, menjadikannya bencana terburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Di balik air bah yang mengamuk, kayu gelondongan yang hanyut menjadi saksi bisu: bukti nyata penebangan hutan secara sembarangan dan tidak terkendali, sesuatu yang selalu dibantah oleh pemerintah daerah.
Deforestasi ini bukanlah bencana alam semata, melainkan hasil dari pengelolaan yang ceroboh, di mana hutan tropis Sumatera Utara—seperti Ekosistem Batang Toru—telah rusak parah akibat aktivitas tambang dan energi.
Kerusakan ekologi di Sumatera Utara sudah tidak bisa ditolerir lagi.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 hektare hutan hilang dalam lima tahun terakhir.
Hutan alam Bukit Barisan yang rawan longsor karena medan yang curam adalah hutan lindung yang tidak boleh ditebang.
Deforestasi di Ekosistem Batang Toru saja melonjak 30 persen dalam periode yang sama, memicu krisis ekologis yang merusak keanekaragaman hayati.
Menurut Global Forest Watch, pada 2025, Sumatera Utara mencatat ribuan alert deforestasi, seperti 1.726 alert antara 14-21 November (21 ha), 15.902 alert antara 30 Oktober-6 November (200 ha), dan 26.462 alert antara 15-22 Agustus (325 ha).
Secara keseluruhan, deforestasi netto di Sumatera Utara mencapai sekitar 6.900 hektare pada 2024, menempatkannya sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan deforestasi terbesar di Indonesia.
Hutan yang seharusnya menjadi penyangga air dan pencegah erosi kini gundul, membuat banjir dan longsor menjadi rutinitas mematikan.
WALHI Sumatera Utara menegaskan bahwa deforestasi tinggi di sekitar wilayah terdampak, diperburuk oleh izin perusahaan yang merusak flora dan fauna endemik.
Selain itu, ekosistem di daerah seperti Dairi dan Pakpak Bharat mengalami kerusakan parah akibat penggundulan masif, yang juga mengancam habitat satwa liar yang berkedok Food Estate, yang diprakarasai oleh LBP.
PT Parna Jaya yang sebagai operator untuk Food Estate seluas 2829 Ha di Sitellu Tali Tali Urang Julu, hanya menanam jagung 5 ha dan kemudian menggunduli hutan ratusan hektar, kayu gelondongan dibawa keluar dari Kabupaten Pakpak Bharat tapi FE tidak pernah berhasil.
Begitupun ribuan hekar hutan yang digunduli oleh PT GRUTI di Parbuluan VI yang menyebabkan konflik dengan masyarakat dan saat ini puluhan aktivis dan masyarakat masih di tahan di Polres Dairi karena mereka membakar asset PT Gruti yang mengakibatkan hilangnya sumber mata air dan kekeringan di musim kemarau.
Pemerintah harus bertanggung jawab atas izin yang dikeluarkan.
Kewenangan penerbitan izin pemanfaatan hutan berada di tangan Kementerian LHK melalui Satgas Penegakan Hukum (Gakkum), bukan di tingkat provinsi seperti DLHK Sumut.
Namun, izin-izin ini sering kali diberikan tanpa selektivitas yang ketat, terutama di wilayah rawan bencana.
Data menunjukkan bahwa per 2024, sekitar 808,65 hektare hutan di Sumatera Utara telah dialihkan untuk area tambang, bagian dari tren nasional di mana mayoritas konversi hutan untuk tambang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Selain itu, terdapat lebih dari 800.000 hektare tambang ilegal di kawasan hutan secara nasional, yang turut berkontribusi pada kerusakan di Sumatera Utara.
Pasca-banjir di Tapanuli Tengah, DLHK Sumut mendesak KLHK untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin pengelolaan hutan, guna mencegah risiko ekologis yang meningkat.
Tuntutan masyarakat, termasuk dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), bahkan menyerukan audit menyeluruh terhadap semua izin konsesi hutan, perkebunan, tambang, dan galian C.
Kebijakan seperti penataan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari seharusnya menjadi prioritas, tapi implementasinya masih lemah, yang terjadi di lapangan adalah kepala daerah dan oknum APH menjadi beking korporasi serta menjadi mafia yang bekerjasama bukannya menjadi regulator yang mengatur regulasi dan menegakkan aturan hukum, justru merekalah pelakunya.
Solusi utama adalah mengembalikan hutan kepada masyarakat hukum adat masing-masing untuk mengelola tanah ulayatnya dengan aturan hukum negara dan kearifan lokal masyarakat hukum adat sendiri, bukan pada negara yang mengelola dengan serampangan tanpa ada batas dan kearifan lokal bekerja sama dengan mafia kayu, mafia tanah dan illegal logging yang justru dilindungi dengan selembar ijin.
UUD 1945 Pasal 18B, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 mengakui hak ulayat, termasuk kemungkinan pengembalian status tanah dari Hak Guna Usaha (HGU) kembali ke masyarakat hukum adat di tanah ulayat masing-masing.
Namun, selama hampir delapan windu negara justru sering abai terhadap hak ini, menyebabkan penurunan luas wilayah hak ulayat akibat penguasaan oleh pihak lain.
Paradigma agraria integratif diperlukan untuk memulihkan hak historis masyarakat adat, memastikan pengelolaan tanah dengan kearifan lokal yang berkelanjutan, dan melindungi kedaulatan pangan.
Sudah saatnya pemerintah berhenti mengabaikan jeritan alam dan masyarakat hukum adat.
Pengembalian tanah ulayat bukan hanya soal keadilan, tapi juga penyelamatan ekosistem berbasis kearifan lokal.
Jika tidak, hujan akan terus menjadi kutukan, dan kayu gelondongan akan tetap menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam menjalankan regulasi yang akhirnya menyengsarakan masyarakat dan merusak ekosistem.
Sesungguhnya, pemerintah yang memberi ijin dan membiarkan penggundulan hutan sebagai penjahat kemanusiaan di tengah bencana ini. (*)